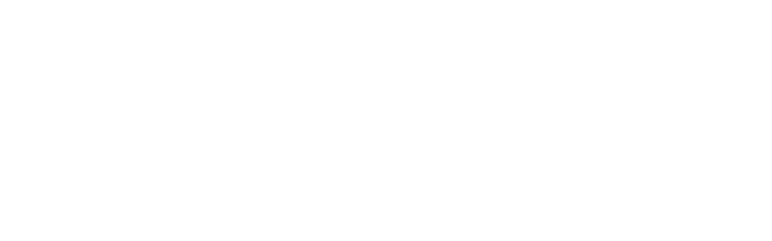Oleh: Fakhrul Fata
Santri Pondok Pesantren Al-Insaniyyah Asal Purworejo Jawa Tengah
Tentu tidak asing bagi Gen Z mendengar kata media sosial. Di mana pun tempat, entah dari yang bocil sampai yang renta pun tak luput dari kehidupan bermedsos. Bahkan orang tua masa kini pun sudah membuatkan akun medsos untuk bayi yang masih dalam kandungan. Cukup menarik hari ini ketika melihat fenomena medsos dengan seabrek postingan, komentar ataupun caption yang bebas nilai. Orang-orang merasa bebas dengan dunia yang telah dibuatnya, merasa lebih leluasa akan tindak virtual dengan memanifestasikan diri dengan sebuah akun.
Katakanlah angkringan 4.0, angkringan kali ini bukan berbentuk fisik dengan berbagai aneka nasi sambal, nasi kucing, wedang jahe atau sekedar sate-satean. Angkringan kali ini menyediakan kebersosialan yang beragam, mulai dari permasalahan, hal-hal jenaka ataupun hanya komentar-komentar pedas dari manusia yang berwujud akun fake. Terlebih hari ini perkembangan for your page (fyp) atau katakanlah hal-hal yang viral masif terjadi. Bagaimana tidak ketika hal itu berisi konten propaganda ataupun dogmatis yang rawan sensitif menimbulkan perpecahan di dunia nyata. Apalagi cuplikan konten agamis yang merujuk pada persoalan teologis ataupun sekedar ikhtilaful ulama.
Saya jadi teringat ketika melihat postingan di suatu akun kubu sebelah. Di situ ada cuplikan video salah satu cendekiawan kami yang diedit ulang kemudian diberi teks dan caption yang mungkin membuat hati para penganutnya tergerak untuk mengatakan ketidaksetujuannya. Ada kata ataupun kalimat yang sensitif, yang bagi kami hal itu merujuk pada penghinaan ataupun sebagai klaim perbuatan dosa yang besar. Captionnya begini “la hawla walakuwata illa billah xKHURAFATx JANGAN DITIRU”.
Jadi, dalam vidionya itu seorang habib sedang mengutip cerita dari suatu syaikh, yang tentunya sudah kredibel dan diakui sebagai alim ulama. Lalu dengan perspektif akun tersebut bahwa hal yang dikatakan itu adalah hanya cerita khayalan dan dongeng belaka. Tentu hal semacam ini menimbulkan polemik yang tiada habisnya di kolom komentar. Ataupun bisa lebih menyebar luas ketika saling share dan fyp.
Banyak komentar pengikutnya (baca: akun tersebut) dengan mengambilkan petikan hadits nabi sebagai alat komennya. Ataupun berupa hujatan pedas dengan mengatakan “pemuda tersesat, lah kok malah tersesat beneran” Walhasil banyak like dan menjadi top komen. Tetapi ketika melihat hadits yang dipaparkan konteksnya bukanlah demikian. Nah, hal-hal inilah ruang kebebasan itu menjadi liberal karna minimnya pengetahuan dan cenderung mengiyakan pendapat yang rasional dan mudah diterima. Namun, sisi intelektualnya disisihkah dan seolah ruang keilmuan itu hanyalah tempat berseteru dan konflik.
Saya pun ikut berkomentar dengan mengatakan bahwa perkataan itu diambil dari seorang syaikh yang pernah bercerita demikian. Tak lama kemudian banyak balasan tak senonoh muncul, ada pula yang ikut mendukung. Mungkin ada sekitar 26 balasan dan 29 like sampai saat ini.
Mereka saling debat kusir yang tak ada ujungnya. Hingga kemudian ada satu komentar begini “tidak akan pernah ketemu (cocok) obrolan ini dengan mereka bang”. Memang sebelum komen saya sudah mewanti-wanti apa yang harus saya ketik, bagaimana penggunaan bahasa komentar yang baik. Sehingga dapat meminimalisir perseteruan. Dan aku pun setuju juga dengan komentar ini. Ya, obrolan ini memang tidak akan pernah habisnya, karena saling mempunyai benang merah yang berbeda. Atau katakanlah yang satunya tidak percaya ada fan ilmu demikian, dan dari kami ilmu itu malah menjadi salah satu cabang ilmu yang sudah tinggi tingkatannya.
Ruang Tanpa Sopan Santun
Demikianlah angkringan 4.0 ini membuat seseorang lebih impersonal tanpa disadari. Sekat-sekal moral itu terbuka lebar dan membiarkan manusia itu layaknya hewan liar. Kita manusia apa bukan sih? Kadang saya berfikiran akan bius ilusi yang seolah-olah di media sosial kita bukan manusia. Layaknya game online, akun yang kita buat hanyalah rekaan semata. Padahal itu adalah perwujudan kita dalam media, persoalan moral dan etika masih lekat atas apa yang kita perbuat.
Pola konflik yang terjadi itu akan terus berulang. Kita merasa bukan sebagai manusia, lebih arogan ketimbang perwujudan aslinya. Sebab kurangnya kesadaran kognitif membuat kekacauan itu terjadi. Apalagi persoalan ITE yang mungkin hanya akan berdampak pada orang-orang di atas sana.
Coba saja bayangkan ketika kekacauan itu lahir dari angkringan-angkringan di pinggir jalan Jogja itu. Misalnya wedang jahe tumpah mengenai pembeli lainnya. Saya rasa tidak akan sedemikian kotornya ketika berucap. Umpatan-umpatan itu saya kira akan redam dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Bahkan orang- di angkringan itu lebih humble dari apa yang dibayangkan. Saling ngobrol tanpa adanya saling kenal. Interaksi-interaksi ramah itu akan terjadi dan malah menjadi suatu relasi yang baik.
Beginilah akhirnya ketika kedua angkringan itu memuat corak yang berbeda. Sekat-sekat moral, dehumanisasi, ataupun impersonal itu akan selalu bermunculan ketika belum pernah jagongan di angkringan pinggir jalan-jalan jogja itu. Humanisasi itu akan muncul secara santun dalam seduhan wedang jahe, nasi kucing dan sate-satean yang lebih mengenyangkan daripada saling klaim salah dan benar.